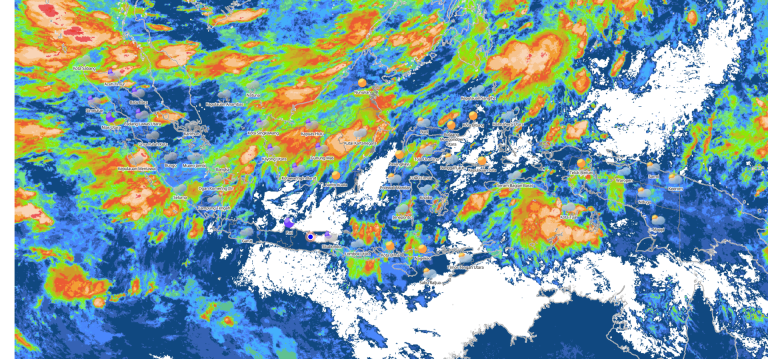Jakarta, kota megapolitan yang menampung jutaan mimpi dan mesin kendaraan, kini menghirup krisis yang tidak bisa lagi diabaikan. Data dari IQAir per 14 Juni 2025 menyebutkan kualitas udara di ibu kota mencapai Indeks PM2.5 sebesar 158, masuk dalam kategori tidak sehat. Itu bukan hanya angka—itu adalah kenyataan yang dihirup saban hari oleh jutaan warga yang tak sempat memilih.
Ketika langit pagi tampak tenang, partikel-partikel mikroskopis yang tak terlihat justru berkumpul lebih padat dari biasanya. Mereka tak berisik, tapi mematikan secara perlahan. PM2.5 adalah polutan dengan diameter di bawah 2,5 mikron, cukup kecil untuk menembus paru-paru dan bersarang dalam aliran darah. Jika racun punya rupa, barangkali inilah bentuk paling diam-diamnya.
Ironisnya, keadaan seperti ini tak lagi mengejutkan. Jakarta nyaris rutin menempati peringkat atas kota paling tercemar di Asia. Setiap pagi, sebelum anak-anak berangkat sekolah, sebelum pekerja menyalakan sepeda motornya, layar aplikasi kualitas udara sudah menunjukkan warna oranye atau merah. Tapi seberapa sering warga bisa benar-benar memilih untuk tidak keluar rumah? Tidak semua bisa bersembunyi di balik purifier dan pendingin ruangan.
Pemerintah DKI Jakarta menyebut telah menggencarkan program uji emisi kendaraan, perluasan transportasi publik, serta urban forest. Tapi program-program ini tak jarang hanya cantik di laporan, tak terasa di napas warga. Padahal 40% pencemaran udara di Jakarta berasal dari transportasi, dan sisanya dari aktivitas industri serta pembangkit listrik di sekitar Jabodetabek. Namun, siapa yang mengevaluasi kontribusi masing-masing secara tegas dan terbuka?
Yang lebih menyedihkan, adalah ketika krisis ini dianggap biasa. Karena polusi bukan seperti gempa atau banjir yang datang tiba-tiba. Ia tumbuh dalam diam, disambut kebiasaan, dipelihara oleh ketidakpedulian. Udara kotor menjadi latar permanen kota: hadir, tapi tidak diurus serius.
Dalam negara yang sedang mengincar visi besar seperti Indonesia Emas 2045, kualitas udara semestinya bukan hanya urusan lingkungan—tapi urusan politik. Ia menyangkut keadilan, sebab warga miskin adalah yang paling terdampak, dan paling sedikit punya pilihan. Ia menyangkut kesehatan, sebab tingginya penyakit ISPA bukan semata soal virus, tapi juga soal ventilasi publik yang tercemar. Ia menyangkut masa depan, karena tidak ada ekonomi yang akan tumbuh dari paru-paru yang sakit.
Maka hari ini, Jakarta bukan hanya mengantre kemacetan. Ia juga tengah mengantre risiko. Dalam antrean panjang itu, ada balita yang sesak napas, ada lansia yang paru-parunya menua lebih cepat, dan ada warga yang tak tahu mengapa batuknya tak kunjung sembuh.
Udara mestinya jadi hak semua orang, bukan kemewahan bagi sebagian. Tapi ketika langit biru hanya bisa dibeli dalam bentuk tabung oksigen, barangkali kita sudah terlalu terbiasa tinggal dalam darurat yang dinormalisasi.